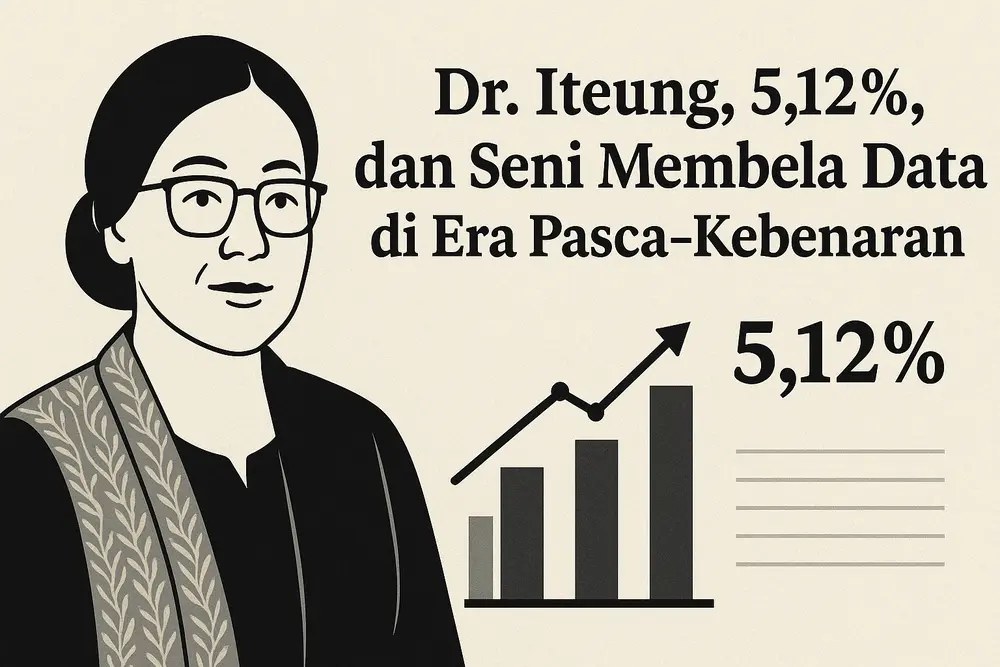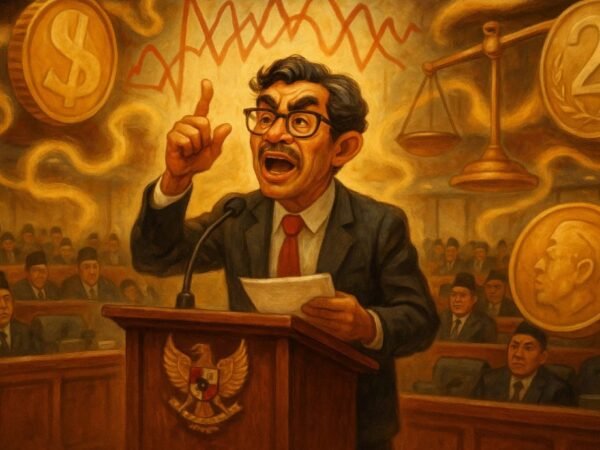Refleksi 9 Hari Menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI
GWS, 8 Agustus 2025
Di ruang konferensi pers yang megah di Gedung BPS, Jakarta, berlangsunglah salah satu pertunjukan paling menarik dalam sejarah ekonomi Indonesia modern. Bukan karena angka-angkanya—meski 5,12% memang mengejutkan—melainkan karena sosok yang duduk di kursi panas: Dr. Iteung Suryani, ekonom lulusan Harvard yang berbicara dengan aksen Sunda yang kental, membela data kontroversial BPS dengan gaya yang unik—setengah profesor, setengah tukang cerita di saung.
“Dangukeun,” katanya membuka sesi yang sudah ditunggu-tunggu itu, “saya tahu kalian semua sudah siap-siap mau menyerang angka 5,12% ini. Saya persilakan. Di Harvard dulu, profesor saya bilang: ‘If you can’t defend your thesis from attacks, then it’s not worth defending.’ Nah, hari ini tesis saya adalah: angka ini benar, caranya sudah tepat, dan keraguan kalian—meski berharga—perlu konteks yang lebih dalam.”
Pernyataan pembuka yang percaya diri, namun disampaikan dengan kerendahan hati khas Sunda. Inilah Nyi Iteung—sosok yang merepresentasikan paradoks Indonesia kontemporer: tradisional tapi modern, lokal tapi global, sederhana dalam penyampaian tapi canggih dalam substansi.
Ketika Angka Menjadi Teater
Pertanyaan pertama datang dari Dr. Bhima Yudhistira, ekonom CELIOS yang skeptis. “Dr. Iteung, bagaimana menjelaskan PMI manufaktur kita konsisten di bawah 50 selama April-Juni—46,7 di April, 47,4 di Mei, 46,9 di Juni—tapi BPS claim industri pengolahan tumbuh 5,68%? Ini kontradiksi yang mendasar.”
Nyi Iteung tersenyum. “Kang Bhima, pertanyaan yang bagus. Ini mengingatkan saya pada dongeng Sufi tentang enam orang buta yang meraba gajah. Yang satu bilang gajah itu seperti tembok karena meraba badannya, yang lain bilang seperti tali karena memegang ekornya, yang lain lagi bilang seperti pohon karena memeluk kakinya. Semua benar dari sudut pandang masing-masing, tapi tidak ada yang melihat gajah secara utuh.”
Dia kemudian menjelaskan dengan lebih rinci: “Mari kita bedah dulu apa itu PMI dan apa itu Produk Domestik Bruto industri. PMI itu kependekan dari Purchasing Managers’ Index—survei kepada manajer pabrik tentang persepsi mereka soal perubahan bulan ke bulan. Angka di atas 50 artinya mereka merasa situasi membaik dibanding bulan lalu, di bawah 50 artinya merasa memburuk.”
“Sekarang, PDB industri itu mengukur nilai total produksi aktual dalam rupiah selama satu tahun penuh. Dia melihat berapa banyak barang yang benar-benar diproduksi, berapa nilai ekonomi yang tercipta dari kegiatan industri.”
“Analoginya begini: Teteh penjual es campur di Cicaheum ditanya, ‘Bulan ini gimana dibanding bulan lalu?’ Dia mungkin bilang ‘menurun’ karena hujan terus, jadi PMI-nya di bawah 50. Tapi kalau ditanya, ‘Pendapatan tahun ini gimana dibanding tahun lalu?’ dia bilang ‘alhamdulillah naik 20%’ karena pelanggan tetap bertambah, lokasi strategis, dan dia sudah punya gerobak baru.”
Lalu dia menghadirkan bukti konkret: “Kapasitas produksi terpakai kita 73,58%—tertinggi dalam setahun. Artinya mesin-mesin di pabrik bekerja hampir tiga perempat waktu, bandingkan dengan kuartal sebelumnya yang cuma 71%. Konsumsi listrik sektor industri naik 8,55%—kalau pabrik sepi, masa listriknya malah naik? Impor mesin naik 28,16%—kalau industri lesu, masa pengusaha malah beli mesin baru?”
“Ini seperti melihat warung yang ramai pelanggan, listriknya nyala terang, tapi si juragan bilang ‘lagi sepi nih bulan ini.’ Mana yang kita percaya, omongannya atau bukti di depan mata?”
Diplomasi Data di Panggung Global
Representatif dari Capital Economics mengajukan tantangan berikutnya: “Dr. Iteung, Capital Economics has long questioned reliability of Indonesian GDP data. How do you respond to international skepticism?”
“Terima kasih atas pertanyaan yang jujur,” Nyi Iteung menjawab dengan nada yang tetap santun tapi tegas. “Keraguan itu wajar dalam ekonomi. Tapi mari kita bedakan antara keraguan yang membangun dengan prasangka yang sudah mengakar.”
“Cara menghitung PDB kita mengikuti standar internasional yang disebut SNA 2008—System of National Accounts 2008. Ini seperti resep masakan internasional yang dipakai negara-negara OECD seperti Amerika, Jerman, Jepang. Kalau resepnya salah, masa semua negara maju pakai resep yang sama?”
Dia melanjutkan dengan penjelasan yang lebih dalam: “Setiap tahun, IMF mengirim tim untuk mengevaluasi cara kita menghitung ekonomi dalam yang disebut Article IV consultation. Ini seperti inspeksi mendadak dari bos besar—kalau caranya salah total, pasti sudah ditegur. Tapi selama ini, tidak ada temuan besar soal cara kita menghitung.”
“Yang menarik, Bank Dunia masih bekerja sama dengan kita untuk mengukur kemiskinan. Kalau data kita tidak bisa dipercaya, masa mereka mau risiko reputasi dengan berkolaborasi?”
Kemudian dia menyentil dengan halus: “Media internasional seperti Fortune, Reuters, dan CNBC memberikan liputan positif soal pertumbuhan kita. Yang meragukan itu analis tertentu—dan keraguan mereka bukan berdasarkan penelaahan mendalam terhadap cara kita menghitung, tapi lebih ke perasaan ‘ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan.’
“Analoginya begini: kalau dokter A periksa saya pakai rontgen, tes darah, dan USG, lalu bilang saya sehat. Tapi dokter B yang cuma lihat dari jauh bilang saya sakit tanpa periksa langsung. Saya akan percaya hasil laboratorium dulu sebelum panik.”
Transparansi dalam Era Pasca-Kebenaran
Wartawan investigatif mengajukan pertanyaan yang lebih menusuk: “Dr. Iteung, Kenapa BPS menghentikan publikasi rutin Indikator Ekonomi sejak Januari? Apakah ini upaya mengurangi keterbukaan saat data menjadi kontroversial?”
Nyi Iteung menghela napas panjang. “Wah, ini kebetulan waktu yang jelek sekali, tapi bukan teori konspirasi. Keputusan itu diambil November 2024, jauh sebelum data kuartal kedua keluar.”
“Mari saya jelaskan masalahnya. Dulu kita menerbitkan data ekonomi yang sama dalam tiga sampai empat format berbeda: Indikator Ekonomi bulanan, Berita Resmi Statistik kuartalan, laporan tahunan, plus versi ringkas untuk media. Bayangkan kalau satu berita ditulis ulang dalam empat gaya berbeda—alih-alih memperjelas, malah bikin pembaca bingung.”
“Keputusannya murni teknis untuk mengurangi kebingungan. Tapi saya akui: waktu pelaksanaannya sangat buruk. Dalam komunikasi publik, persepsi itu penting. Marshall McLuhan pernah bilang: ‘The medium is the message.’ Cara kita menyampaikan informasi sama pentingnya dengan informasinya itu sendiri.”
Dia kemudian menekankan: “Pelajaran yang dipetik: keputusan soal keterbukaan harus dikomunikasikan jauh-jauh hari dengan penjelasan yang jelas. Kita akan perbaiki ini ke depan.”
“Yang penting, data mentahnya tetap tersedia lengkap di situs web. Yang berkurang hanya kemasannya, bukan isinya. Keterbukaan bukan soal berapa banyak buku yang diterbitkan, tapi soal seberapa mudah masyarakat mengakses informasi yang akurat.”
Kenyataan Lapangan versus Kenyataan Statistik
Pengusaha yang hadir mengajukan pertanyaan yang paling menyentuh: “Dr. Iteung, di lapangan PHK naik 32%, kepercayaan konsumen turun, tapi pemerintah klaim pertumbuhan 5,12%. Di mana putusnya?”
Inilah momen paling krusial. Nyi Iteung terdiam sejenak, ekspresinya berubah lebih serius. “Ini pertanyaan paling penting hari ini, karena menyentuh kehidupan nyata masyarakat, bukan cuma angka di atas kertas.”
“Mari kita uraikan satu per satu. PHK naik 32%—itu memang mengkhawatirkan dan saya tidak akan minimalisir dampaknya pada keluarga-keluarga yang terkena. Tapi konteksnya: tahun dasar 2024 itu secara historis rendah karena pemulihan pasca-COVID. Dalam angka absolut, level PHK sekarang masih di bawah masa sebelum pandemi.”
Dia melanjutkan dengan analogi yang mudah dipahami: “Bayangkan tahun lalu cuma 100 orang di-PHK di sebuah kota, tahun ini jadi 132 orang. Secara persentase naik 32%—terdengar mengerikan. Tapi dulu sebelum COVID, rata-rata 200 orang per tahun. Jadi meski naik dari tahun lalu, masih jauh lebih baik dari normal.”
“Sekarang soal kepercayaan konsumen versus belanja aktual—ini fenomena psikologi ekonomi yang menarik. Indeks kepercayaan konsumen turun dari 121,1 menjadi 117,5, tapi indeks penjualan eceran riil naik 1,19%, transaksi uang elektronik naik 6,26%. Artinya orang bilang pesimis tapi tetap belanja.”
“Daniel Kahneman, ekonom peraih Nobel, menyebut ini stated preference versus revealed preference—apa yang orang katakan versus apa yang benar-benar mereka lakukan sering berbeda. Seperti orang bilang mau diet tapi tetap beli gorengan setiap hari.”
Kemudian dia memberikan konteks yang lebih luas: “Pertumbuhan ekonomi itu seperti kue yang membesar. Tapi kue yang lebih besar tidak otomatis artinya semua orang kebagian potongan yang lebih besar. Yang penting ke depan, manfaat pertumbuhan harus lebih merata. Pertumbuhan tanpa pemerataan itu tidak berkelanjutan.”
Metodologi dalam Pusaran Politik
Ekonom akademis mengajukan pertanyaan teknis: “Dr. Iteung, bisakah Anda menjelaskan secara rinci pembobotan yang menghasilkan angka 5,12% ini?”
“Dengan senang hati,” Nyi Iteung menjawab sambil membuka laptopnya. “Mari kita bongkar dapur perhitungan PDB seperti membedah resep masakan.”
“Konsumsi rumah tangga bobotnya 57% dari total PDB—ini terbesar karena memang sebagian besar ekonomi kita digerakkan belanja masyarakat. Dia tumbuh 4,97%, didorong Hari Besar Keagamaan Nasional dan liburan sekolah. Bayangkan betapa ramenya mal, restoran, dan tempat wisata saat lebaran dan libur panjang.”
“Investasi atau pembentukan modal tetap bruto bobotnya 32%—ini uang yang dipakai beli mesin, bangun pabrik, infrastruktur. Dia tumbuh 6,99%, tertinggi dalam empat tahun. Konsumsi pemerintah cuma 8% dan malah turun 0,33%.”
“Kunci penting: pertumbuhan investasi ini bukan rekayasa statistik. Impor mesin naik 28%, impor barang modal 31%, belanja modal pemerintah 30%. Ini transaksi riil yang bisa diverifikasi—ada dokumen bea cukai, ada kontrak pembelian, ada laporan keuangan perusahaan.”
“Untuk penyesuaian musiman, kita pakai sistem yang disebut X-13ARIMA-SEATS—standar internasional yang dipakai negara maju. Tapi efek Ramadan kita sesuaikan manual karena tanggalnya bergeser setiap tahun, tidak seperti Natal yang selalu 25 Desember.”
Dia kemudian menunjukkan laptop: “Dokumen lengkap metodologi ada 400 halaman—tersedia gratis di situs web dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Tidak ada yang dirahasiakan.”
Taruhan Reputasi dalam Wacana Publik
Kemudian datang pertanyaan yang paling personal dan tajam: “Dr. Iteung, sebagai lulusan Harvard, apakah Anda tidak khawatir mempertaruhkan reputasi dengan membela data yang mungkin cacat?”
Ruangan sunyi. Nyi Iteung menatap langsung ke kamera, dengan ekspresi yang serius namun tenang.
“Itu pertanyaan yang adil dan berat. Reputasi saya sebagai ekonom memang sedang dipertaruhkan di sini.”
“Tapi saya tidak akan membela data yang saya tahu salah. Selama enam tahun di Harvard, saya belajar mempertanyakan segalanya, termasuk otoritas. Kalau saya curiga ada manipulasi atau kesalahan mendasar, saya akan mengungkapnya tanpa ragu, meski harus berhadapan dengan atasan.”
“Kenyataannya: 5,12% itu mengejutkan, tapi bukan mustahil. Indonesia punya keunggulan struktural—populasi muda, urbanisasi yang terus berlanjut, pembangunan infrastruktur besar-besaran. Kuartal kedua adalah pertemuan beberapa faktor positif yang kebetulan bersamaan.”
Dia kemudian mengutip Carl Sagan: “There’s a quote from Carl Sagan: ‘Extraordinary claims require extraordinary evidence.’ Yang saya bawa hari ini bukan klaim luar biasa—ini data yang komprehensif, cara menghitung yang tepat, dan penjelasan yang masuk akal.”
“Kalau data kuartal ketiga menunjukkan penurunan drastis, maka kita perlu menyelidiki apakah kuartal kedua memang anomali. Tapi berdasarkan bukti yang ada sekarang, 5,12% bisa dipertanggungjawabkan.”
Intermezzo: Pelajaran dari Warung Kopi
Di tengah sesi yang tegang, Nyi Iteung tiba-tiba bercerita: “Izinkan saya cerita sebentar. Di kampung saya di Lembang ada warung kopi Pak Asep. Suatu hari dia bilang omzetnya naik 50% dalam sebulan. Tetangga-tetangga pada curiga, ‘Masa sih? Perasaan sepi-sepi aja.’ Ternyata pas diselidiki, dia mulai jual gorengan, buka dari subuh sampai malam, dan kebetulan ada proyek jalan di depan warung jadi tukangnya pada nongkrong.”
“Apakah omzetnya bener naik 50%? Ya. Apakah terlihat aneh dari luar? Ya. Apakah ada alasan logis? Ya juga.”
“Ekonomi Indonesia kuartal kedua seperti warung Pak Asep itu. Ada faktor-faktor yang bersamaan: stimulus pemerintah, liburan panjang, investasi infrastruktur, dan strategi ekspor menghindari tarif Amerika. Semuanya nyata, semua terukur.”
Epilog: Antara Keraguan dan Sinis
Dalam pernyataan penutup, Dr. Iteung berkata: “Mari kita bedakan antara keraguan yang sehat dan kecurigaan yang merusak. Keraguan bertanya: ‘Bagaimana Anda tahu?’ Kecurigaan bilang: ‘Anda tidak mungkin tahu apa-apa.'”
“Data ekonomi bukan fiksi ilmiah. Ada kegiatan ekonomi nyata di belakangnya—orang bekerja, perusahaan berinvestasi, barang diproduksi, jasa dikonsumsi. Tugas kita adalah mengukur kegiatan ini seakurat mungkin.”
“Aristoteles bilang: ‘Ciri pikiran terdidik adalah mampu mempertimbangkan suatu gagasan tanpa harus menerimanya.’ Pertimbangkanlah angka 5,12% ini. Pertanyakan, uji, validasi. Tapi jangan tolak hanya karena tidak sesuai intuisi.”
Kemudian dengan senyum khas Sunda, dia mengakhiri: “Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup memuaskan rasa ingin tahu kalian. Kalau masih ada pertanyaan, pintu saya selalu terbuka. Hatur nuhun.”
Refleksi: Teater Data dalam Demokrasi
Apa yang kita saksikan dalam “pertunjukan” Nyi Iteung ini sebenarnya adalah gambaran kecil dari tantangan yang lebih besar: bagaimana menyampaikan kebenaran ilmiah dalam era pasca-kebenaran, di mana setiap angka bisa dipolitisasi dan setiap penjelasan bisa dicurigai sebagai propaganda.
Nyi Iteung—dengan latar belakang akademis internasional tapi kebijaksanaan lokal—merepresentasikan upaya menjembatani kesenjangan antara ketepatan teknis dan pemahaman publik. Dia tidak sekadar membela angka, tapi membela prinsip bahwa wacana berdasarkan bukti masih mungkin dilakukan di tengah polarisasi politik.
Yang menarik dari penampilannya adalah bagaimana dia menggunakan perumpamaan universal—dari dongeng Sufi hingga teori psikologi ekonomi—untuk menjelaskan konsep yang rumit. Ini menunjukkan bahwa kecanggihan tidak harus berarti elitisme.
Pertanyaan yang tersisa: apakah masyarakat masih bisa mempercayai lembaga? Apakah cara menghitung yang tepat cukup untuk membangun kepercayaan? Dan yang paling penting: dalam era di mana setiap narasi bisa digugat, bagaimana kita membedakan antara keraguan yang membangun dan kecurigaan yang merusak?
Jawaban Nyi Iteung sederhana tapi mendalam: “Terus bertanya, tapi terus belajar.” Meragukan boleh, tapi jangan sampai keraguan membuat kita berhenti berpikir kritis. Dan yang terpenting, jangan biarkan kecurigaan menghancurkan kemungkinan untuk mencari kebenaran bersama.
Seperti kata pepatah Sunda: “Tatali paranti tatata, tatata paranti tatali”—segala sesuatu saling terkait. Data ekonomi, kepercayaan publik, cara menghitung ilmiah, dan kebijaksanaan tradisional—semuanya bagian dari ekosistem yang lebih besar dalam pencarian kebenaran kolektif.
Dan mungkin inilah pelajaran terpenting dari drama ekonomi ini: kebenaran bukan komoditas yang bisa dibeli atau dijual, tapi proses yang harus dijalani bersama dengan kejujuran, keterbukaan, dan—yang paling penting—kerendahan hati untuk mengakui ketika kita salah.
Hatur nuhun, Nyi Iteung. Pelajaran hari ini tidak hanya soal angka 5,12%, tapi soal bagaimana kita berdemokrasi dengan data, berargumen dengan fakta, dan mencari kebenaran dengan hati nurani. (*)
Note: Tulisan opini ini berasal dari grup WhatsApp dan diterbitkan editorindonesia.com dengan izin pihak pertama yang membagikannya.